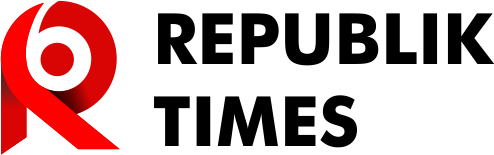Republiktimes.com – Fenomena boikot produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel cukup lama menggema di Indonesia. Masyarakat yang digerakkan oleh solidaritas terhadap isu kemanusiaan, berbondong-bondong menyerukan penghentian konsumsi terhadap berbagai merek yang diduga berafiliasi dengan Israel. Di permukaan, gerakan ini tampak sarat idealisme. Namun, kalau kita telisik lebih dalam, muncul pertanyaan kritis: benarkah gerakan ini murni, atau ada penumpang gelap yang ikut menumpang arus?
Boikot di Indonesia kerap bergerak tanpa koordinasi terpusat dan minim verifikasi. Daftar produk yang harus diboikot beredar luas lewat media sosial, seringkali tanpa kejelasan sumber dan bukti yang sahih. Di tengah kekaburan informasi ini, ada perusahaan-perusahaan yang justru memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisinya di pasar.
Melalui tulisan ini, saya coba merasionalisasi mengapa Gerakan ini banyak penumpang gelapnya, bahkan melibatkan ormas keagamaan, media Islam dan Yayasan-yayasan yang mengaku mewakili umat Islam.
Boikot Ternyata ‘Akal-Akalan’ Persaingan Bisnis
Di tengah derasnya seruan boikot, muncul fenomena manipulasi yang cukup mencolok. Salah satu contohnya terjadi dalam industri air minum dalam kemasan. Sebuah merek yang tengah berusaha memperluas pasarnya secara diam-diam mendorong masuknya pesaing utamanya ke dalam daftar produk yang harus diboikot. Melalui sebuah Yayasan yang mengaku mewakili konsumen muslim, media Islam, bahkan organisasi keagamaan Islam, mereka mengaitkan pesaing tersebut dengan isu-isu yang tengah menjadi perhatian publik. Padahal dalam kenyataannya, produk pesaing itu tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Ini adalah strategi yang tidak fair—memanfaatkan gelombang emosi masyarakat untuk menjatuhkan lawan bisnis.
Fenomena ini membuka sisi lain dari gerakan boikot di Indonesia yang jarang dibahas: bahwa solidaritas yang seolah-olah murni ternyata sering menjadi kendaraan untuk kepentingan ekonomi tertentu. Tidak sedikit perusahaan yang mendadak membungkus diri mereka dengan citra “nasionalis”, “pro-kemanusiaan”, atau “halal” dalam berbagai materi kampanye mereka. Mereka berlomba-lomba menunjukkan keberpihakan, bukan semata-mata karena nilai yang dianut, tetapi demi menggaet simpati konsumen di tengah situasi sosial yang sensitif.
Celakanya, karena masyarakat sering terbawa arus emosi tanpa verifikasi, tak sedikit yang akhirnya terjebak dalam permainan ini. Boikot yang seharusnya menjadi alat perjuangan justru bergeser menjadi alat persaingan bisnis terselubung. Publik dijadikan pion dalam pertarungan merebut pangsa pasar, sementara perusahaan-perusahaan yang bermain di balik layar menuai keuntungan besar tanpa harus mengotori tangan mereka sendiri.
Boikot Seperti Kiasan ‘Menembak Kaki Sendiri’
Lebih parah lagi, boikot yang dilakukan secara emosional tanpa pertimbangan mendalam justru kerap berujung pada bencana sosial di dalam negeri. Banyak produk yang diboikot sebenarnya diproduksi di pabrik-pabrik lokal, dikerjakan oleh ribuan tenaga kerja Indonesia. Ketika penjualan anjlok drastis, efek dominonya cepat terasa: produksi dikurangi, pabrik ditutup, dan PHK massal pun terjadi.
Boikot semacam ini ibarat menembak kaki sendiri. Alih-alih melemahkan kekuatan asing, kita justru menghancurkan sumber penghidupan buruh dan karyawan di negeri sendiri. Yang menderita bukan pemilik modal besar di luar negeri, melainkan para pekerja kecil yang hidupnya bergantung pada gaji bulanan.
Bayangkan dua restoran: satu terafiliasi dengan kebijakan yang ingin kita lawan, satu lagi hanyalah cabang waralaba lokal yang dikelola oleh pengusaha kecil Indonesia. Tanpa riset, kita memboikot keduanya. Akibatnya, restoran lokal tutup, para pekerjanya kehilangan pekerjaan, dan ekonomi lokal terguncang. Inilah realita yang sering terjadi ketika boikot dilakukan tanpa strategi dan akal sehat.
Penutup
Maka, dalam menghadapi seruan boikot, kita perlu lebih kritis. Gerakan ini harus berbasis pada data valid, pemahaman rantai pasok, dan kesadaran penuh atas dampak yang mungkin ditimbulkannya. Target harus jelas, tujuannya harus nyata, dan strateginya harus mengutamakan keadilan—bukan malah menjadi alat persaingan bisnis terselubung.
Kalau tidak, kita hanya akan menjadi bagian dari drama besar di mana emosi kita dimanfaatkan oleh para pemain yang tersenyum di balik layar. Mereka menang, kita—rakyat biasa—yang menanggung akibatnya. Akhirnya, setiap kali kita diajak untuk memboikot, penting untuk bertanya: “Siapa yang benar-benar kita lawan? Dan siapa yang diam-diam diuntungkan?”[]
Masithoh/Mahasiswa Hukum Islam Program Doktor (HIPD) UII Yogyakarta