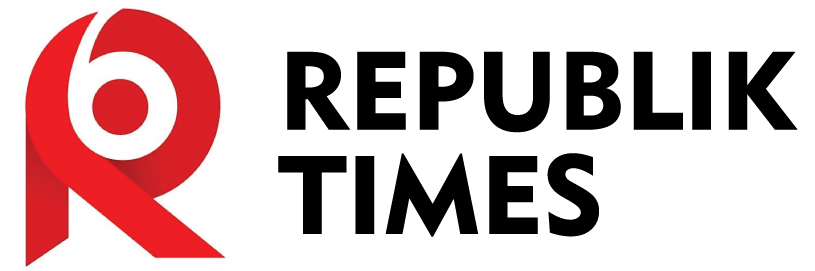Republiktimes.com – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, baru saja melemparkan usulan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dilakukan melalui DPRD, dalam HUT Golkar ke-61 (5/12) silam. Bahkan, pernyataan Bahlil tersebut juga dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, agar demokrasi minim ongkos dan tidak ditentukan oleh orang-orang yang berduit.
Mengenai hal tersebut, Pakar politik, Arifki Chaniago, menilai, usulan tersebut merupakan langkah mundur dari capaian demokrasi elektoral Indonesia. Menurutnya, Pilkada langsung memang tidak sempurna, tetapi mengembalikannya ke DPRD bukanlah jawaban tepat, karena hanya memindahkan persoalan dari ruang publik ke ruang elite, dan publik akan membacanya sebagai pengurangan hak memilih.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, bahwa narasi “efisiensi pemilu” sering dipakai dalam diskusi elite, tetapi hampir tidak pernah menjadi keluhan utama rakyat di daerah. Yang justru dikeluhkan adalah buruknya tata kelola kampanye, lemahnya penegakan hukum Pemilu, hingga minimnya edukasi politik.
“Kalau vas bunga jatuh karena raknya goyang, yang harus diperbaiki itu raknya, bukan menyembunyikan bunganya ke gudang. Demokrasi kita bermasalah bukan karena rakyat memilih langsung, tetapi karena infrastruktur politiknya tidak diperkuat,” ungkap Arifki, pada Senin (8/12/2025).
Menurutnya, usulan kembali ke DPRD membuka pintu lebar untuk politik transaksional. Di mana mekanisme pemilihan oleh segelintir anggota DPRD membuat akuntabilitas kepala daerah tidak lagi diarahkan kepada rakyat, tapi kepada elite yang memilih.
“Risikonya sederhana, kepala daerah lebih sibuk menjaga suara di ruang tertutup ketimbang bekerja untuk suara publik. Kita pernah hidup dalam model itu dan tidak ada nostalgia yang perlu dirayakan,” tegasnya.
Dari sisi komunikasi politik, wacana ini juga dinilai tidak peka terhadap suasana publik. Di tengah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai dan lembaga legislatif, menawarkan pengalihan kewenangan pemilihan kepala daerah ke DPRD justru memperburuk jarak antara elite dan warga.
“Ini semacam pesan yang tidak sinkron. Ketika publik menuntut transparansi dan partisipasi yang lebih besar, justru muncul wacana yang mengembalikan proses politik ke ruangan tertutup. Secara persepsi, ini langkah yang sangat kontra dengan arus publik,” jelas Arifki.
Tak hanya itu, ia juga menambahkan, bahwa wacana ini tampak lebih sebagai manuver politik ketimbang kajian serius. Karena dengan Pilkada lewat DPRD kita tak lagi mengenal figur seperti Jokowi, Anies, Sandi, Ahok, Risma, dan lainnya. Pernyataan ini, tentu akan berdampak terhadap dinamika UU Pemilu dan kalkulasi parpol melihat potensi pemilu 2029.
“Kalau wacana sebesar ini muncul hanya sebagai lemparan awal tanpa desain lengkap, itu menunjukkan bahwa ini sekadar diskursus awal UU Pemilu tahun 2026 yang sedang dilakukan ‘tes ombak’. Aturan tidak boleh dikelola dengan metode ‘lempar dulu, lalu lihat siapa saja yang marah’ dan selanjutnya dibatalkan,” ungkapnya.
Arifki, yang juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini, menegaskan, bahwa demokrasi lokal tidak perlu dirombak ke belakang, melainkan diperbaiki ke depan. Yang dibutuhkan adalah perbaikan regulasi, penguatan pengawasan, literasi politik, dan pembiayaan politik yang transparan. Bukan mencabut hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya. Kita memperbaiki mesin, bukan mengganti penumpang.
“Dengan bola wacana telah digulirkan, ia menilai respons publik dan partai lain akan menentukan apakah ide ini akan semakin mengecil atau justru menjadi perdebatan nasional. Yang jelas, menurutnya, demokrasi Indonesia layak mendapat argumen yang lebih kuat daripada sekadar alasan tidak mau pusing regenerasi kepemimpinan nasional yang berasal dari daerah,” tutup Arifki.