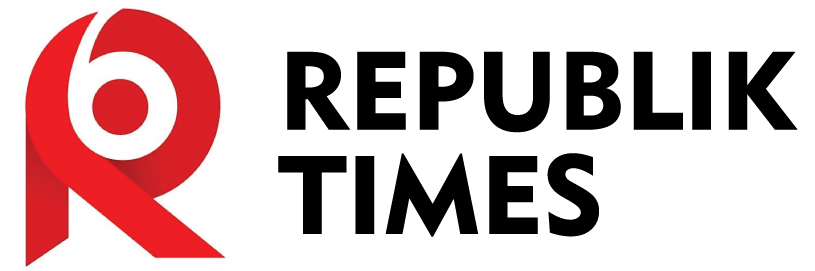Republiktimes.com – Persoalan lingkungan saat ini menjadi isu global yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia (ekonomi, politik, sosial, dan spiritual). Krisis ekologis bukan sekadar akibat dari kemajuan teknologi atau industrialisasi yang tak terkendali, melainkan cerminan dari krisis moral dan spiritual umat manusia.
Dalam konteks ini, pemikiran filsuf Muslim kontemporer Ṭaha Abdurraḥman menawarkan suatu paradigma etis yang segar dan orisinal dalam memahami hubungan antara manusia dan alam. Melalui konsep falsafah al-I’timaniyyah (filsafat amanah), Ṭaha Abdurrahman berupaya merekonstruksi etika Islam agar mampu menjawab tantangan kemanusiaan dan lingkungan pada era modern.
Manusia dan Lingkungan dalam Perspektif Islam
Dalam pandangan Islam, lingkungan (al-bi’ah) bukanlah sekadar ruang hidup bagi manusia, tetapi merupakan wadah keberadaan (wujud) dan tempat berlangsungnya tugas kekhalifahan. Alam menjadi panggung tempat manusia menjalankan tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah di bumi. Sejak awal, hubungan manusia dengan alam bersifat timbal balik: manusia bergantung pada alam untuk kelangsungan hidupnya, sementara alam bergantung pada manusia untuk dijaga dan dikelola sesuai nilai-nilai ilahi.
Perhatian manusia terhadap lingkungan mengalami perkembangan historis yang panjang. Pada tahap awal, manusia hanya berinteraksi dengan alam secara praktis, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Namun seiring kemajuan peradaban dan munculnya revolusi industri, hubungan tersebut berubah menjadi eksploitasi. Alam dipandang sebagai objek ekonomi, bukan lagi mitra spiritual. Dari sinilah muncul kerusakan ekosistem, pencemaran, dan ketidakseimbangan ekologis yang kini mengancam kehidupan manusia.
Lingkungan dalam Al-Qur’an dan Sunnah
Al-Qur’an secara konsisten menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Beberapa ayat menggunakan istilah “bawa’” yang berarti tempat tinggal atau tempat menetap, menunjukkan peran bumi sebagai rumah bagi manusia. Sebaliknya, istilah “fasad” digunakan untuk menandai segala bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia terhadap bumi.
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.” (QS. Ar-Rum: 41)
Hadits Nabi Muhammad SAW. juga menegaskan tanggung jawab manusia terhadap bumi. Rasulullah melarang segala bentuk pengrusakan, menganjurkan penghijauan, serta memerintahkan agar sumber daya digunakan secara bijak. Dalam Islam, merawat bumi merupakan bentuk ibadah dan perwujudan dari rasa syukur atas nikmat Allah.
Kritik Ṭaha Abdurraḥman terhadap Etika Modern
Taha Abdurraḥman mengkritik keras etika modern Barat yang menyingkirkan agama dari kehidupan. Etika modern, menurutnya, dibangun atas dasar rasionalitas instrumental yang berorientasi pada manfaat material dan kepentingan individu. Akibatnya, manusia modern kehilangan kesadaran spiritual dan menempatkan dirinya sebagai pusat alam semesta, bukan bagian dari ekosistem ciptaan Tuhan.
Filsafat Barat mengandalkan tiga prinsip logika klasik: identitas (identity), nonkontradiksi (non-contradiction), dan kausalitas (causality). Ṭaha menggantinya dengan tiga prinsip spiritual-etis yang ia sebut prinsip etimaniah (iʾtimaniyyah):
- Prinsip Syahadah (Kesaksian): Segala sesuatu ada karena kesaksian terhadap kebenaran dan keesaan Tuhan. Manusia menjadi saksi atas dirinya, alam, dan Sang Pencipta. Alam bukan benda mati, melainkan bagian dari sistem kesaksian universal terhadap Allah.
- Prinsip Amanah (Tanggung Jawab): Manusia tidak memiliki alam, melainkan hanya memegang amanah untuk memeliharanya. Amanah ini menuntut sikap moral, spiritual, dan ekologis. Prinsip ini menggantikan “prinsip nonkontradiksi” dalam logika Barat: jika akal menolak kontradiksi, maka iman menolak pengkhianatan terhadap amanah.
- Prinsip Tazkiyah (Penyucian): Etika sejati menuntun manusia untuk menyucikan diri dan memperbaiki lingkungan. Melalui tazkiyah, manusia menyeimbangkan dimensi spiritual dan material hidupnya. Tujuan akhirnya bukan sekadar kemajuan teknologi, tetapi kesempurnaan moral dan harmoni kosmis.
Hubungan Wahyu dan Lingkungan
Ṭaha Abdurrahman melihat bahwa keadilan Allah telah terwujud di alam sebelum manusia diciptakan. Alam diciptakan dalam keseimbangan (mizan) yang sempurna. Oleh karena itu, tugas manusia bukan menguasai alam, tetapi menjaga keseimbangan tersebut.
Al-Qur’an menampilkan empat tingkatan relasi manusia dengan lingkungan:
- Tingkat fungsional, di mana alam melayani kebutuhan manusia (ayat-ayat tentang taskhir).
- Tingkat kontemplatif, di mana manusia diajak merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam.
- Tingkat estetis, yang menumbuhkan rasa kagum terhadap keindahan ciptaan.
- Tingkat ekologis, di mana manusia menjaga harmoni dan keberlanjutan makhluk hidup.
Ayat-ayat seperti QS. Ar-Rahman: 7–9 dan QS. Al-Hijr: 19 menegaskan prinsip keseimbangan (tawāzun) sebagai dasar keberlangsungan alam semesta.
Krisis Lingkungan dan Krisis Etika
Bagi Ṭaha Abdurraḥman, krisis lingkungan merupakan akibat langsung dari krisis etika. Modernitas dengan ideologi materialisme dan sekularisme telah menumbuhkan hubungan komodifikasi (tasyyi‘) antara manusia dan alam. Alam tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan barang yang bisa dieksploitasi. Hubungan manusia dengan alam berubah menjadi hubungan ekonomi yang menimbulkan tiga bentuk keterasingan:
- Keterasingan dari alam – karena eksploitasi sumber daya alam.
- Keterasingan dari sesama manusia – karena kompetisi ekonomi yang tak beretika.
- Keterasingan dari diri sendiri – karena hilangnya spiritualitas dan makna hidup.
Dampaknya dapat dilihat dalam pemanasan global, pencemaran udara, krisis air, dan punahnya spesies. Semua ini, menurut Ṭaha Abdurrahman, bukan hanya kegagalan ilmiah, tetapi kegagalan moral.
Etika Lingkungan dalam Perspektif I’timaniyah
Etika lingkungan yang ditawarkan Ṭaha berakar pada iman, tanggung jawab, dan penyucian diri. Ia menegaskan tiga prinsip moral yang menjadi dasar bagi etika ekologis Islam:
- Etika sebagai esensi kemanusiaan. Akal bukan penentu hakikat manusia, melainkan moralitas.
- Etika yang bersifat universal. Ia mencakup hubungan manusia dengan alam, sesama manusia, dan Tuhan.
- Etika yang bersumber dari agama. Hanya wahyu yang mampu menumbuhkan kesadaran ekologis sejati, karena di dalamnya terkandung nilai amanah dan tanggung jawab kosmis.
Penutup
Ṭaha Abdurraḥman memandang krisis lingkungan sebagai panggilan untuk menghidupkan kembali ruh etika Islam. Alam bukan sekadar sumber daya, tetapi bagian dari sistem kesaksian terhadap keesaan Tuhan. Manusia sebagai khalifah Allah harus menjaga keseimbangan ekologis sebagai wujud pengamalan amanah dan tazkiyah.
Dengan demikian, penyelamatan lingkungan dalam pandangan Ṭaha Abdurrahman bukan hanya tugas teknis, tetapi tugas spiritual dan moral yang menghubungkan manusia dengan Penciptanya. Etika lingkungan Islam, sebagaimana digagas Ṭaha, mengembalikan manusia pada hakikatnya sebagai makhluk yang amanah, yang memelihara bumi sebagai tanda cinta dan ketaatan kepada Allah SWT.[]
Edo Segara Gustanto/Mahasiswa Hukum Islam Program Doktor UII Yogyakarta