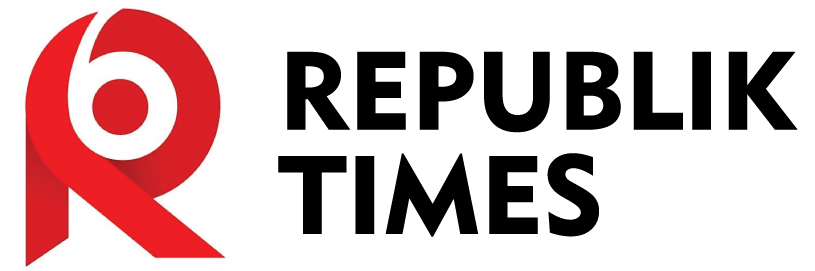Yogyakarta, Republiktimes.com – Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah lama menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa. Indonesia sejatinya telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam memberantas korupsi, terutama melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, di tengah keseragaman norma hukum tersebut, publik justru menyaksikan realitas yang paradoksal: penanganan kasus korupsi oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering kali berbeda, baik dari segi kecepatan, pendekatan, hingga hasil akhirnya.
Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar di ruang publik: jika undang-undangnya sama, mengapa praktik penegakan hukumnya tidak seragam? Pertanyaan ini penting, bukan sekadar untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan prinsip keadilan.
Perbedaan Mandat dan Budaya Kelembagaan
Secara normatif, kepolisian, kejaksaan, dan KPK sama-sama memiliki kewenangan dalam penanganan perkara korupsi. Namun, perbedaan mandat institusional dan desain kelembagaan membuat cara kerja ketiganya tidak identik. Kepolisian memiliki tugas utama penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan berperan sebagai penuntut umum sekaligus memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus tertentu, sementara KPK dirancang sebagai lembaga khusus dengan fokus pada korupsi yang bersifat sistemik dan melibatkan aktor strategis.
Di luar aspek formal, budaya kelembagaan juga berpengaruh besar. Kepolisian dan kejaksaan merupakan institusi besar dengan struktur hierarkis yang panjang serta beban perkara yang sangat beragam. Dalam konteks ini, korupsi sering kali diperlakukan sebagai salah satu jenis kejahatan di antara banyak prioritas lainnya. Sebaliknya, KPK dibentuk dengan budaya organisasi yang lebih ramping, fokus, dan berorientasi pada dampak serta efek jera.
Perbedaan budaya ini memengaruhi gaya penanganan perkara. KPK dikenal dengan pendekatan yang agresif, cepat, dan terbuka ke publik, sementara kepolisian dan kejaksaan cenderung lebih prosedural dan tertutup. Bagi publik, perbedaan tersebut sering diterjemahkan sebagai perbedaan komitmen, meskipun dalam banyak kasus akar persoalannya lebih kompleks.
Faktor Politik, Diskresi, dan Relasi Kekuasaan
Penegakan hukum tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa. Faktor politik dan relasi kekuasaan kerap memengaruhi bagaimana sebuah kasus korupsi ditangani. Di sinilah perbedaan antarpenegak hukum menjadi semakin nyata. Kepolisian dan kejaksaan, sebagai bagian dari struktur pemerintahan, tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika politik dan birokrasi. Diskresi penegak hukum, yang secara teoritis diperlukan untuk fleksibilitas, dalam praktik bisa membuka ruang ketidakseragaman.
KPK, setidaknya dalam desain awalnya, dibangun dengan tingkat independensi yang lebih tinggi. Kewenangan penyadapan, penuntutan mandiri, serta mekanisme rekrutmen yang relatif berbeda membuat KPK memiliki daya tawar lebih kuat dalam menghadapi intervensi. Namun, dinamika politik belakangan menunjukkan bahwa independensi tersebut juga tidak sepenuhnya kebal dari tekanan kekuasaan.
Perbedaan tingkat independensi inilah yang kemudian tercermin dalam keberanian mengambil perkara besar, menentukan tersangka, hingga strategi komunikasi publik. Ketika satu lembaga terlihat tegas dan progresif, sementara yang lain tampak lamban atau ragu-ragu, publik pun dengan mudah menarik kesimpulan adanya standar ganda, meskipun realitas hukumnya lebih berlapis.
Menuju Keseragaman Substantif Penegakan Hukum
Perbedaan cara penanganan korupsi oleh tiga institusi penegak hukum tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyeragamkan aturan di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah keseragaman substantif dalam penegakan hukum, yakni kesamaan visi, integritas, dan orientasi pada keadilan. Harmonisasi kewenangan, penguatan koordinasi, serta kejelasan mekanisme supervisi antar lembaga menjadi kunci untuk mengurangi tumpang tindih dan disparitas.
Lebih dari itu, reformasi penegakan hukum harus menyentuh aspek sumber daya manusia dan budaya organisasi. Profesionalisme, perlindungan terhadap penegak hukum yang berintegritas, serta sistem penghargaan dan sanksi yang adil perlu diperkuat. Tanpa itu, undang-undang yang sama akan terus menghasilkan praktik yang berbeda.
Sebagai penutup, publik tidak menuntut keseragaman gaya, melainkan kesetaraan dalam keadilan. Selama hukum ditegakkan secara konsisten, transparan, dan bebas dari intervensi, perbedaan institusi tidak akan menjadi masalah. Namun, ketika perbedaan itu melahirkan kesan tebang pilih, maka yang terancam bukan hanya kredibilitas lembaga penegak hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara hukum itu sendiri.[]
Edo Segara Gustanto/Mahasiswa S3 Hukum Islam Program Doktor UII, Yogyakarta